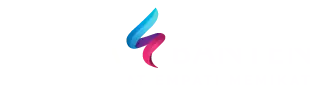Pelitabanten.com – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa haram mempelajari dan mengajarkan kitab ghairu muktabar, karena tidak merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadits serta memuat ajaran selain Ahlu Sunnah wal Jama’ah. Fatwa tersebut dibacakan pada hari Kamis, (23/11/2017) setelah proses Sidang Paripurna VI di Gedung Serbaguna MPU Aceh.
Pertama, Kitab Ghairu Muktabar, sebagaimana disebutkan dalam fatwa, adalah kitab-kitab yang memuat ajaran Mujassimah dan Musyabihah, seperti kitab Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah, Kitab Fathul Majid karya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, Fatawa Albani, kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahab, Syarah al-Aqidah al-Washitiyah karya Muhammad Sholeh al-Utsaimin, dan sejenisnya.
Kedua, kitab yang dianggap memuat ajaran hulul dan ittihad seperti kitab Insan Kamil karya Abdul Karim bin Ibrahim al-Jili, kitab Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, kitab Kasyf al-Asrar karya Muhammad Shaleh bin Abdullah al-Minangkabawi, dan kitab sejenisnya.
Ketiga, kitab yang memuat ajaran yang memusuhi para sahabat seperti kitab Man la yahdhur al-Faqih dan kitab al-Imamah wa Tabshirah min al-Hijrah karya Muhammad bin Baqwai al-Qumi, dan sejenisnya.
Keempat, kitab yang memuat ajaran Ushul al-Tsalasah (Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa shifat) seperti kitab Qutul Qulud karya al-Hasan bin Huzaini, kitab Kifa Nafhamu al-Tauhid karya Muhammad Basyamil, dan sejenisnya.
Fatwa larangan untuk mempelajari dan mengajarkan kitab yang dianggap Ghairu Muktabar ini bertolak dari pertimbangan untuk menghindari kegamangan, dan kebingungan, bahkan perpecahan dalam masyarakat Aceh. Sebagai tindak lanjut dari fatwa ini, MPU Aceh bahkan menghimbau agar kitab ghairu muktabar tersebut tidak menjadi materi para da’i, materi pengajian, bahkan dilarang untuk menjualnya di toko buku, dan pemerintah lokal diminta untuk mengawasi kitab-kitab yang masuk ke Aceh.
Isu pelarangan dan pemberangusan terhadap buku, baik itu buku keagamaan, politik, dan ideologi tertentu bukanlah kisah baru dalam sejarah intelektual-akademik dan sejarah kekuasaan politik. Kita dengan mudah menemukan kisah pelarangan buku yang dianggap berseberangan dengan ideologi penguasa atau ajaran yang dianggap bertentangan dengan faham resmi keagamaan di manapun dan dalam kurun waktu di masa lalu. Secara umum, pelarangan terhadap buku datang dari kekuasaan yang dominan dan totalitarian, atau dari klaim ‘kebenaran’ ajaran dari mazhab yang resmi sehingga karya pemikiran yang dianggap berseberangan dilarang untuk dibaca, dikaji, dan disebarkan. Kekhawatiran yang berlebihan dari sebuah rezim kekuasaan ini cermin dari ‘ketakutan’ terhadap kritik kekuasaan yang sedang berlangsung atau mazhab resmi keagamaan yang berlindung di balik terminologi ‘ajaran sesat dan menyesatkan’.
Di negeri ini, pelarangan buku sudah berlangsung lama bahkan sejak masa kolonial hingga era reformasi dan begitu juga dengan sejarah Islam, pelarangan terhadap sebuah faham sudah berlangsung sejak masa kekhalifahan bahkan kisah yang paling masyhur ialah peristiwa ‘inkuisisi’ atau Mihnah pada 833 M (281 H) yang dilakukan Khalifah Al-Makmun terhadap keyakinan para ulama yang dianggap tidak sesuai dengan mazhab resmi penguasa ketika itu dengan memaksa ulama tertentu agar mengadopsi pandangan Mu’tazilah. Inkuisisi tersebut terus berlangsung bahkan setelah wafatnya khalifah Al-Makmun hingga masa tiga khalifah setelahnya selama 16 tahun. Di saat Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa, ia mengakhiri hukuman dan melepaskan para ulama yang tidak tunduk pada kebijakan khalifah sebelumnya dari penjara dan merekrut beberapa di antaranya untuk ikut di dalam pemerintahan.
Bila kita cermati fatwa MPU Aceh mengenai kitab Ghairu Muktabar ini termuat beberapa paradoks dan inkonsistensi yang kuat terutama klaim bahwa kitab-kitab yang tersebut tidak sesuai dengan ajaran Ahlu Sunnah wa Jama’ah. Di dalam fatwa tersebut karya Ibnu Arabi, Abdul Karim al-Jili dan Ibnu Taimiyah dianggap sebagai kitab Ghairu Muktabar karena bertentangan dengan akidah Ahlu Sunnah. Pertanyaan sederhana bisa diajukan, apakah Ibnu Taimiyah bukan ulama yang disegani dalam tradisi Sunni? Apakah Ibnu Arabi dan Abdul Karim al-Jili tidak termasuk ulama tasawuf yang diperhitungkan di dalam tradisi tasawuf falasafi dari kalangan Sunni? Atas dasar apa ketiga ulama penting di dalam tradisi Sunni ini dianggap keluar dari akidah Ahlu Sunnah wal Jama’ah? Tiga pertanyaan krusial ini bisa menjadi titik tolak untuk membantah fatwa MPU Aceh mengenai karya-karya Ibnu Arabi, Abdul Karim al-Jili, dan Ibnu Taimiyah sebagai karya yang dikategorikan kitab ghairu muktabar.
Di dalam tradisi akademik, penilaian terhadap pemikiran seorang ulama dan karya kesarjanaannya hanya mungkin apabila kita telah membaca keseluruhan karyanya, baik karya yang utuh dalam bentuk buku maupun karya-karya yang lain, seperti, risalah-risalah, bahkan catatan-catatan pendek yang pernah ditulis semasa hidupnya, atau bahkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama tersebut terhadap para muridnya, yang biasa dikumpulkan dalam bentuk buku setelah mereka wafat. Saya akan memulai dengan membentangkan secara ringkas posisi Ibnu Taimiyah di dalam tradisi Sunni, lalu diakhiri dengan Ibnu Arabi dan Abdul Karim al-Jili, karena kedua yang terakhir memiliki orientasi faham tasawuf falsafi yang searah, al-Jili di dalam karya-karyanya mengelaborasi lebih lanjut tasawuf falsafi Ibnu Arabi. Kedua ulama tasawuf falsafi ini dicatat sebagai tonggak penting dalam tradisi tasawuf di kalangan Sunni.
Kita mulai dengan yang pertama, sejauh manakah kesahihan pernyataan bahwa karya Ibnu Taimiyah bertentangan dengan akidah Ahlu Sunna wal Jama’ah. Para penafsir Ibnu Taimiyah sepakat menempatkan Ibnu Taimiyah sebagai ulama penting dalam tradisi Sunni, meskipun ketokohannya dalam tradisi kesarjanaan Islam penuh kontroversi karena gaya berargumentasinya yang polemis di dalam karya-karyanya. Gaya yang polemis, vulgar, hiperbolik dan bombastis pada Ibnu Taimiyah tidaklah mengurangi substansi mengenai apa yang ingin ia sampaikan, serta pembelaannya yang kukuh terhadap sumber utama dalam Islam; al-Qur’an dan al-Hadits. Kontroversi yang meliputi Ibnu Taimiyah tersebut terlihat dari kenyataan bahwa ia seringkali menyerang secara langsung suatu aliran dan pemikiran, termasuk praktik-praktik kaum sufi klasik yang dianggap menyimpang dari ajaran pokok Islam serta kritiknya yang tajam terhadap falsafah yang dikembangkan oleh para ulama Kalam yang dianggapnya sangat dipengaruhi oleh Aristoteles dalam logika dan tradisi filsafat Neoplatonisme.
Gaya yang sangat vulgar dalam kritiknya terhadap pemikiran yang dipengaruhi Aristoteles dan Neoplatonisme dalam filsafat Islam serta kaum sufi yang dianggapnya menyimpang bisa dijelaskan dari latar historis ketika Ibnu Taimiyah hidup dan berkarya, suatu situasi di mana umat Islam sedang dalam situasi krisis akibat serangan dari kaum Tatar serta perasaan bahwa umat Islam mengalami kemunduran luar biasa, sebuah situasi yang sering disebut dengan ‘self-defeating’, perasaan mengalami kekalahan akibat runtuhnya pusat-pusat penting peradaban Islam, seperti Baghdad akibat serangan kaum Tatar. Di dalam situasi krisis yang dialami umat Islam saat itu, ia memandang bahwa para ulama dan penguasa ikut bertanggung jawab secara langsung atas situasi kemunduran Islam.
Selain dikenal polemis di dalam karya-karyanya, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai tokoh pembaru dan pemurni yang menghendaki umat Islam kembali kepada apa yang diamalkan dan pemahaman yang otentik dari generasi awal Islam atau Kaum Salaf. Seruannya untuk melakukan purifikasi ajaran Islam dengan kembali ke praktik-praktik keagamaan kaum salaf inilah yang kemudian dapat diringkaskan dengan mottonya yang sangat terkenal, “al-ruju ila al-Kitab wa al-Sunnah”, yaitu kembali ke Kitab Suci dan Sunnah Nabi serta meneladani kaum salaf yang saleh (al-salaf al-shalih), yaitu merujuk pada tiga generasi pertama Islam meliputi para sahabat Nabi, para tabi’in atau generasi kedua, dan tabi’in tabi’in atau generasi ketiga.
Di sisi lain, ia juga menyerukan untuk kembali membuka pintu ijtihad agar umat Islam keluar dari kejumudan dan stagnasi. Di dalam evaluasinya mengenai kemunduran umat Islam pada masa ia hidup, secara politik pandangan Ibnu Taimiyah sangat menekankan integrasi umat, yaitu bertolak dari faham ‘Jama’ah’, yaitu faham persatuan menyeluruh umat Islam, terlepas dari pandangan masing kelompok dan golongan. Di hadapan perselisihan dan perbedaan ia tetap menegaskan untuk pentingnya melihat sisi-sisi persamaan dalam perbedaan.
Keluasan erudisinya atas tradisi keilmuan Islam membuatnya dikenal sebagai ulama yang subur dalam berkarya, terutama bekerja keras melalui karya untuk merumuskan kembali pemahaman keagamaan yang sesuai dengan Kitab Suci dan Sunnah. Ikhtiar yang dilakukannya melalui karya keilmuan ini juga membuat ulama terkenal dari Mesir Jalaluddin al-Suyuthi (satu dari dua penulis tafsir Jalalayn) meringkaskan karya Ibnu Taimiyah, ‘Juhd al-Qarihah fi Tajrid al-Nashihah”. Imam as-Suyuhti berikhtiar melalui karya tersebut untuk menyebarkan pemikiran Ibnu Taimiyah agar dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, sebab ia melihat pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah perlu didukung dan disebarkan.
Meskipun Ibnu Taimiyah dianggap figur kontroversial karena kritiknya terhadap aliran pemikiran yang dianggapnya berseberangan dengan gaya yang hiperbolik, tekanannya yang kuat untuk membatasi model penafsiran takwil atau interpretasi metaforis yang seringkali dipraktikkan kaum sufi terhadap teks-teks suci, sikapnya yang realis terhadap sejarah Islam hingga ia secara gigih melawan pemikiran spekulatif yang dikembangkan di dalam ilmu Kalam dan falsafah bukan berarti kitab-kitabnya tidak boleh dipelajari, dibaca secara serius, serta mencari bagian-bagian penting dari argumentasinya yang relevan dalam mengembangkan tradisi pemikiran keagamaan.
Menyebut karya Ibnu Taimiyah sebagai karya yang ghairu muktabar merupakan sebuah tindakan yang serampangan secara akademik dan anti-perkembangan keilmuan Islam. Bagaimanapun kontroversialnya figur ini dalam sejarah pemikiran Islam, ia layak diperhatikan karena usahanya yang tulus dan sungguh-sungguh untuk merenungkan tradisi keislaman secara bertanggungjawab, dan kita sebagai pembacanya juga meresponsnya dengan cara yang bertanggungjawab dan akademik pula, bukan sebaliknya dengan melarang untuk mengelaborasi karya-karya Ibnu Taimiyah.
Di bagian lain, tradisi tasawuf falsafi merupakan tonggak penting yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Tasawuf falsafi yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi dan kemudian Abdul Karim al-Jili merupakan usaha sistematis untuk mentsrukturkan pengalaman ruhani kaum sufi dalam bentuk disiplin pengetahuan keislaman. Terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh tentang karya Ibnu Arabi dan Abdul Karim al-Jili, kita dapat mengajukan pertanyaan sederhana, yaitu di dalam tradisi tasawuf Sunni, dapatkah kita mengabaikan orisinalitas karya-karya dari Ibnu Arabi dan Abdul Karim al-Jili?
Ibnu Arabi dan al-Jili, keduanya, adalah kanon dalam tradisi tasawuf falsafi, suka atau tidak suka terhadap karya kedua ulama tersebut, tidak dapat dihindari keduanya harus diapresiasi entah dalam bentuk mengafirmasi ajaran-ajaran yang termuat di dalam karya keduanya atau sebaliknya melakukan kritik ilmiah terhadap keduanya, mengafirmasi dan mengkritik keduanya menunjukkan bahwa keduanya penting untuk ditanggapi sebagai salah satu kontribusi penting dalam tradisi tasawuf falsafi, karena itu tidak ada jalan untuk menghindari keduanya, kecuali dengan mengabaikan karyanya sebagai penanda inkompetensi keilmuan dalam menghadapi apa yang telah ditulis keduanya serta pengaruh yang ditimbulkannya dalam disiplin tasawuf di dunia, tak terkecuali nusantara. Mengabaikan Ibnu Arabi dalam tasawuf sama dengan mengabaikan warisan penting kesarjanaan Islam di masa lalu yang tetap hidup; terus dibaca, dikaji, diteliti bahkan oleh sebuah perkumpulan pemerhati Ibnu Arabi sedunia, yaitu Ibnu Arabi Society. Ibnu Arabi Society dipersembahkan secara khusus untuk eksplorasi terhadap karya-karya Ibnu Arabi, baik secara tematik maupun implikasinya terhadap praktik-praktik dalam dunia tarekat kesufian.
Keberatan terhadap Ibnu Arabi umumnya datang dari pembacaan terhadap karya Ibnu Arabi Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyah, kedua karya Ibnu Arabi yang seringkali disalahfahmi dan kontroversial sejak lama, dan al-Jili sebenarnya hanya melanjutkan saja pokok-pokok ajaran Ibnu Arabi yang termuat di dalam kedua karya Ibnu Arabi dengan menuliskannya di dalam kitab Insan Kamil, sebuah karya al-Jili yang kemudian berpengaruh terhadap penyebaran ajaran martabat tujuh melalui tulisan Imam al-Kurani ke wilayah nusantara terutama wilayah Aceh berkat Abdul Rauf Singkel. Konsep martabat tujuh inilah yang seringkali kali dianggap menyimpang dari akidah Ahlu Sunnah sejak lama oleh para ulama yang tidak sepakat dengan doktrin wujudiyah. Bukanlah hal baru apabila fatwa ini secara terang-terangan menyebut Ibnu Arabi dan al-Jili sekaligus, karena keduanya sejalan dalam erudisinya terhadap ajaran wujudiyah.
Di dalam sejarah keilmuan tasawuf, al-Jili mempelajari Ibnu Arabi justru atas anjuran gurunya Syaikh Ismail al-Jabarti, di dalam kesaksiannya di dalam kitab Maratib al-Wujud, al-Jili menyatakan bahwa sang guru menyerukan para muridnya untuk mempelajari karya-karya Ibnu Arabi. Kisah ini penting untuk dikemukakan untuk mengingatkan pentingnya karya-karya yang diwariskan oleh Ibnu Arabi dalam tradisi tasawuf sehingga para murid Syaikh al-Jabarti diwajibkan membaca karya-karyanya serta diminta bersabar di dalam menjalani tangga pemahaman di saat menelaah kitab-kitab Syaikh al-Akbar tersebut. Jadi bukanlah kebetulan apabila al-Jili di kemudian hari menjadi salah satu komentator penting atas karya-karya Ibnu Arabi, dan dianggap salah satu yang cemerlang melakukan sistematisasi atasnya melalui karya yang dikenal luas para pengkaji tasawuf, yaitu kitab Insan Kamil.
Ibnu Arabi memang seringkali dituduh sesat oleh para ulama Syari’ah karena dianggap melakukan penyelewengan-penyelewengan dari doktrin dasar Islam, khususnya yang terjadi di kalangan kaum sufi meskipun oleh para pengikutnya ia disebut dengan gelar al-syaikh al-akbar (guru yang agung). Tuduhan ini sangat beralasan mengingat ungkapan-ungkapan yang digunakan Ibnu Arabi di dalam karya-karyanya banyak sekali menggunakan kata kiasan (matsal) dan perlambang (ramz). Ungkapan-ungkapan Ibnu Arabi yang demikian itu harus didekati dengan model interpretasi metaforis atau tafsir batini (ta’wil). Model pendekatan ta’wil inilah yang menjadi metode pokok yang digunakan oleh kaum sufi di dalam menafsirkan teks-teks suci, baik itu al-Qur’an maupun Hadits Nabi.
Apakah model interpretasi ta’wil ini dianggap salah atau keliru, sebenarnya, meskipun menggunakan metode ta’wil, kaum sufi tetap berpegang teguh dengan sumber-sumber suci tersebut. Sebagai konsekuensinya, penerapan metode ta’wil dalam penafsiran teks-teks suci tidak terpaku pada bunyi-bunyi tekstual tapi melihat lebih dalam makna dibalik teks yang zhahir, ungkapan Ibnu Atha’illah mewakili kesetiaan metodologis ini dalam dialognya dengan Ibnu Taimiyah, bahwa teks secara literal serupa jasad kasar dan makna teks serupa ruh, dan kaum sufi berikhtiar untuk menangkap ruh dari sebuah teks bukan jasad kasarnya.
Kemudian inilah pangkal-tolak perbedaan mendasar dan sengketa antara ulama sufi dengan ulama Syari’ah. Pendapat ini diperkuat oleh argumen Ibnu Atha’illah, bahwa memahami teks Ibnu Arabi secara harfiah terkadang menyebabkan kekeliruan. Penafsiran harfiahlah yang mendasari penilaian terhadap Ibn Arabi, salah seorang imam yang terkenal akan kesalehannya. Ibnu Arabi tentunya menulis dengan gaya simbolis; sedangkan para sufi adalah orang-orang ahli dalam menggunakan bahasa simbolis yang mengandung makna lebih dalam dan gaya metaforis yang menunjukkan tingginya kepekaan spiritual, serta kata-kata yang menghantarkan rahasia mengenai fenomena yang tak terlihat.
Pembelaan Ibnu Atha’illah terhadap Ibn Arabi seraya menegaskan bahwa ia salah seorang ulama terhebat yang mengenyam pendidikan di Dawud al-Zahiri, seperti Ibn Hazm al-Andalusi, seorang yang pahamnya selaras dengan metodologi tentang hukum Islam, tetapi meskipun Ibn Arabi seorang Zahiri (menerjemahkan hukum Islam secara lahiriah), metode yang ia terapkan untuk memahami hakekat adalah dengan menelisik apa yang tersembunyi, mencari makna spiritual (thariq al- batin), guna mensucikan batin (tathir al-batin).
Meskipun demikian tidak seluruh pengikut mengartikan secara sama apa-apa yang tersembunyi. Agar kita tidak keliru atau lupa, menurut Ibnu Atha’illah, ulangilah bacaan kita mengenai Ibn Arabi dengan pemahaman baru akan simbol-simbol dan gagasannya. Pembaca akan akan menemukannya sangat mirip dengan al-Qusyairi. Ibnu Arabi, tegas Ibnu Atha’illah, telah menempuh jalan tasawuf di bawah payung al-Quran dan Sunnah, sama seperti hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mengusung perdebatan mengenai perbedaan mendasar mengenai iman dan isu-isu ibadah, namun menilai usaha ini kurang menguntungkan dan bermanfaat di kemudian hari.
Sejalan dengan ucapan itu, Al-Ghazali berpendapat: cara tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui qalbu, bukan jasad. Bukan berarti hati dalam bentuk fisik yang dapat melihat, mendengar atau merasakan secara gamblang. Melainkan, dengan menyimpan dalam benak, rahasia terdalam dari Allah Yang Maha Agung dan Besar, yang tidak dapat dilihat atau diraba. Sesungguhnya ahli sunnahlah yang menobatkan syaikh sufi, Imam Al-Ghazali, sebagai Hujjatul Islam, dan tak seorang pun yang menyangkal pandangannya bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa Ihya Ulumuddin nyaris setara dengan al-Quran. Dalam pandangan Ibn Arabi dan Ibn al-Farid, taklif atau kepatuhan beragama laksana ibadah yang mihrab atau sajadahnya menandai aspek batin, bukan semata-mata ritual lahiriah saja. Karena apalah arti duduk berdirinya dalam sholat sementara hati kita dikuasai selain Allah. Allah memuji hamba-Nya dalam al-Quran:”(Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya”; dan Ia mengutuk dalam firmanNya: “(Yaitu) orang-orang yang lalai dalam sholatnya”. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Arabi saat mengatakan: “Ibadah bagaikan mihrab bagi hati, yakni aspek bathin, bukan lahirnya”.
Seorang muslim takkan bisa mencapai keyakinan mengenai isi al-Quran, baik dengan ilmu atau pembuktian itu sendiri, hingga ia membersihkan hatinya dari segala yang dapat mengalihkan dan berusaha untuk khusyuk. Dengan demikian Allah akan mencurahkan ilmu ke dalam hatinya, dan dari sana akan muncul semangatnya. Seseorang yang tulus adalah ia yang menyibukkan diri di hadapan Allah dengan mematuhi-Nya. Barangkali yang menyebabkan para ahli fiqih mengecam Ibnu Arabi adalah karena kritik beliau terhdap keasyikan mereka dalam berargumentasi dan berdebat seputar masalah iman, kasus-kasus hukum yang aktual dan kasus-kasus yang baru dihipotesakan atau dibayangkan padahal belum terjadi.
Ibnu Arabi mengkritik demikian karena ia melihat betapa sering hal tersebut dapat mengalihkan mereka dari kejernihan hati. Ibnu Arabi mengingatkan bahwa: ”Siapa saja yang membangun keyakinannya semata-mata berdasarkab bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif, maka ia membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan. Karena ia akan selalu dipengaruhi oleh sangahan-sangahan balik yang konstan. Keyakinan bukan berasal dari alasan logis melainkan tercurah dari lubuk hati.” Karena itu keyakinan tidak akan tumbuh karena rasionalitas, melainkan ditimba dari kedalaman qalbu.
Apresiasi para ulama terhadap karya Ibnu Arabi tidak bisa dikatakan remeh, karya Ibnu Arabi Fusus al-Hikam bahkan dikomentari oleh sejumlah ulama terkemuka sesudahnya seperti Sadr al-Din al-Qunawi (wafat. 671 H), ‘Afif al-Din al-Tilimsani (wafat. 690 H), Mu’ayyid al-Din al-Jundi (wafat. 700 H), Sa‘d al-Din al-Farghani (wafat. 700 H), Kamal al-Din al-Zamalkani (wafat. 727 H), Dawud al-Qaysari (wafat. 751 H), Kamal al-Din al-Qashani (wafat. 751 H), Sayyid ‘Ali al-Hamadani (wafat. 766 H), Khwaja Muhammad Parsa (wafat. 822 H) sahabat dekat Shah Naqshband, Mawlana Jami (wafat. 898), Isma‘il al-Anqarawi (wafat. 1042 H), ‘Abd al-Ghani al-Nabulusi (wafat. 1144 H).
Kritik terhadap Ibnu Arabi yang dilakukan oleh Burhan al-Din al-Biqa‘i (wafat 885 H) berjudul, Tanbih al-Ghabi ila Takfir Ibn ‘Arabi wa Tahdhir al-‘Ibad min Ahl al-‘Inad, dijawab oleh Imam al-Suyuthi di dalam kitab, Tanbih al-Ghabi fi Tanzih Ibn ‘Arabi, bahwa para ulama di masa lalu dan masa kini menjadi terbelah di dalam memandang posisi Ibnu Arabi, kelompk pertama menganggapnya sebagai wali Allah seperti Ibnu Atha’illah al-Sakandari, dan Afif al-Din al-Yafi’i, sementara kelompok lainnya menganggapnya sebagai ahli bid’ah, terutama kebanyakan mereka adalah ahli syari’at, seperti al-Dhahabi di dalam kitab al-Mizan.
Sikap yang terbelah dari dua kelompok terhadap Ibnu Arabi ini didamaikan oleh Ibnu Atha’illah melalui kitab Lata’if al-Minan (fi Manaqib Abi al-‘Abbas al-Mursi wa Shaykhihi Abi al-Hasan al-Shadhili), bahwa syaikh Izz al-Din pada mulanya bersikap sebagaimana para ahli syari’at yang secara terburu-buru menempatkan Ibnu Arabi serta kaum sufi pada umumnya sebagai sesat. Di saat Syaikh Abu al-Hasan al-Syadzily pulang dari menunaikan ibadah haji lalu menemui Syaikh Izz al-Din di kediamannya dengan mengucapkan salam serta solawat nabi, dan duduk bersama lalu menyatakan bahwa Ibnu Arabi merupakan seorang Mujtahid terakhir, mendengar itu, Sharaf al-Din al-Munawi menjawab bahwa Ibnu Arabi merupakan salah seorang wali Allah, itu diakui baik oleh para pengagumnya maupun oleh para penentangnya. Menurut Ibnu Atha’illah, ketika syaikh al-Islam Izz al-Din ibn Abd Salam memahami apa yang sebenarnya diucapan dan dianalisa oleh Ibn Arabi, menangkap dan mengerti makna sebenarnya dibalik ungkapan simbolisnya, ia segera memohon ampun kepada Allah swt atas pendapatnya sebelumnya dan menokohkan Muhyiddin Ibn Arabi sebagai Imam Islam.
Tiga ulama yang diakui di dalam tradisi Sunni ini; Ibnu Taimiyah, Ibnu Arabi, dan Abdul Karim al-Jili secara konsisten merujuk kepada sumber-sumber suci dalam Islam, yaitu al-Qur’an dan Hadits Nabi, serta Ibnu Taimiyah berusaha mengusung agenda reformasi Islam dengan semboyan kembali pada kitab suci dan Sunnah, berikhtiar sepanjang hidupnya bahkan rela dipenjara beberapa kali oleh penguasa pada zamannya demi melakukan purifikasi ajaran Islam, termasuk kritik yang tak kenal lelah terhadap penguasa yang tidak adil. Sementara di bagian lain, Ibnu Arabi dan al-Jili telah berjasa merekontruski pengalaman para pengamal tasawuf dalam karya yang sistematis dan lengkap melalui magnum opus keduanya Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyah, serta kitab Insan Kamil. Karena itu fatwa ini menjadi tidak relevan untuk perkembangan tradisi keilmuan Islam dan sepenuhnya menjadi antitesa terhadap watak dasar etos intelektualisme Islam yang terbuka, serta telah terbukti memiliki kesanggupan menyerap berbagai tradisi yang baik dari sejumlah peradaban hingga menjadi bagian penting kekayaan peradaban Islam. Wallahu’alambishawab.
Narasumber: Abdul Hakim, S.Fil, M.A., Alumni Pesantren Raudhatul Hikam, Cibinong, Bogor