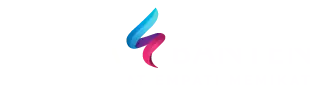Pelitabanten.com – Iah, masih ingatkah engkau, kali pertamanya kita berjumpa? Pada waktu itu, ketika matahari tepat di atas ubun-ubun, langit membiru, diperindah oleh awan tipis yang melayang ringan menyerupai sekelompok malaikat yang terbang tanpa mengapakan sayap-sayapnya. Masih jelas dalam benakku, engkau terlihat lemah, matamu berkejap laksana mata duyung yang sedang bersedih hati, kendati demikian aku terpesona oleh raut wajahmu, yang jelita itu. Semenjak itulah, wajahmu tertanam kuat dalam sanu bariku.
Selang beberapa hari, engkau bilang padaku; bahwa kamu dilanda sakit, dan benar saja tubuhmu tergolek tanpa daya, di atas kasur. Selang beberapa hari setelah engkau berobat ke rumah sakit, kesehatanmu membaik, dan jiwaku pun turut membaik—karena tak lagi mencemaskanmu.
Iah, atas cintaku padamu, engkau jangan ragu. Kau adalah bagian dari hidupku, sakitmu adalah penderitaanku, setiap tetes air mata yang menggenangi kedua bilah pipimu, aku turut merasakan. Deritamu adalah kepedihanku.
Pada suatu pagi, tubuhmu tergolek, engkau sakit kembali. Ibumu menangis, Iah. Tangis ibumu merambat ke empat penjuru mata angin, menyelinap masuk ke dalam telinga para tetangga, mengetuk jiwa mereka. Dalam waktu yang sejenak rumahmu telah dipadati orang yang menjengukmu. Sungguh engkau memiliki ibu yang begitu cinta padamu. Di sini aku pun turut merasakan kesakitan engkau. Tak terbayang olehku jika sakit itu berujung kematian. Dan aku bisa gila karenanya.
Iah, pada suatu malam. Aku lihat engkau tergolek tak berdaya, sedangkan malaikat maut berputar-putar di atasmu. Tiba-tiba matamu terbuka, tubuhmu perlahan bergerak dan duduk, seakan kamu hendak mengusir malaikat maut itu. Kini malaikat maut berputar-putar di ubun-ubunmu, dan engkau menjulurkan tangan ke atas, membela diri mempertahankan nyawamu yang hendak diambil malaikat itu. Tetapi, engkau terlalu lemah dan malaikat maut terlalu kuat. Malaikat maut menarik nyawamu melalui ubun-ubunmu seperti seorang petani yang menarik gulma di padang ilalang. Matamu mendelik, tubuhmu mengejang, untuk selanjutnya tak bergerak untuk selama-lamanya.
Iah aku menangis, suaraku lirih namun menurih jiwa siapa saja yang mendengar tangisanku itu. Setelah engkau dikebumikan orang-orang menghiburku, “sabar ya,” demikian kata mereka, dan perkataan mereka semakin menyayat hatiku. Terdengan orang-orang membaca ayat suci Alquran layaknya dalam sebuah perlompaan sahut-menyahut, melepas kepergianmu ke alam baka. Dan semua itu menambah berat bebanku, jiwaku terasa robek-robek, tercabik tak lagi berbentuk.
Iah, aku bangun dari lelap tidurku, ternyata itu hanyalah mimpi. Aku hubungi engkau melalui seluler, dan engkau berkata padaku; bahwa engkau baik-baik saja. Namun, mimpi itu begitu nyata, hingga air mataku yang keluar adalah nyata pula. Demikianlah orang yang sedang jatuh cinta, sehingga kecemasan yang sekian lama terpendam, kemudian muncul dalam bentuk mimpi.
Aku pernah membaca buku Psikoanalisis karya Freud; menurutnya mimpi menjelma sebagai dampak dari kejiwaan manusia seperti kecemasan, dan kecemasan itu disimpan di alam bawah sadar, yang berujung pada munculnya kecemasan itu dalam bentuk mimpi.
Iah, aku sungguh mencemaskanmu, kau jangan sakit-sakit lagi. Dan kabar gembira itu kembali aku dapatkan, bahwa engkau baik-baik saja, bahkan sakit yang selama ini engkau derita. Kini, telah menjauh darimu. Namun, entahlah kecemasan itu terkadang datang lagi. Ah, mungkin karena aku begitu sayang pada engkau.
Kini engkau telah terbebas dari rasa sakit, tubuh engkau yang semula layu sekarang segar kembali. Kecantikanmu, membuat mata keranjang laki-laki tak putus-putusnya menatapmu. Dan engkau gembira, “bukan main cantiknya kamu,” ujar seorang laki-laki padamu, dan tawa renyahmu meledak. Aku pun tersenyum kuning, senyum bercampur rasa cemburu.
Engkau berceloteh padaku, tentang para lelaki yang memuji keelokanmu, aku pun tahu, jiwa engkau dilanda kebahagiaan, sebab setiap perempuan akan bersuka-cita manakala dirinya dibilang cantik, terlebih oleh makhluk yang berlainan jenis kelamin.
Pada suatu malam dalam kamarmu disinari cahaya lampu listrik, neon. Engkau duduk di atas kursi sofa sedangkan di hadapanmu terpampang sebuah cermin, engkau melihat pantulan wajahmu yang terpampang nyata dalam cermin itu. Engkau tersenyum dan berdecak, mengagumi kejelitaan diri-sendiri. Pun aku mengerti demikian kodrat perempuan, ia begitu gemar bersolek diri, dan memuji kecantikan diri sendiri.
Baiklah, Iah. Aku punya sekelumit cerita, dahulu di tanah Yunani, pernah hidup seorang dewi jelita, dan dewi itu dikenal orang sebagai Dewi Narsis. Pada suatu waktu yang entah. Dewi Narsis jalan-jalan di pesisir. Ia teringat akan kecantikannya yang puji oleh para dewa-dewi. Perlahan kaki mungil Dewi Narsis tercelup ke air laut, ia hendak bercermin melalui riak air laut.
Dewi Narsis merundukkan wajahnya, terpantullah wajahnya itu dipermukaan air laut. Dewi Narsis terpukau oleh kecantikannya sendiri, ia melotot tanpa berkedip, terpesona olah wajahnya sendiri. Tiada terasa arus air laut telah membawa Dewi yang malang itu ketengah laut. Ketika Dewi Narsis sadar akan bahaya yang tengah menimpanya, namun terlambat, dirinya terlanjur terhanyut, dan Sang Dewi, diketemukan mati terapung di atas permukaan air laut itu.
“Oh jadi engkau mempersamakan aku dengan Dewi Narsis,” ujarmu ketus.
Aku tersenyum, aku lihat pipimu merona, mungkin lantaran amarah. Namun, dengan demikian wajahmu semakin menjadi-jadi cantiknya, bahkan beberapa kali lipat.
“Bukan. Bukan begitu maksudku. Aku hendak berkata padamu, bahwa Narsis adalah salah satu penyakit jiwa. Orang Narsis terlalu gila akan pujian, bahkan ia akan tersinggung jika ada yang bilang bahwa wajahnya tidak cantik. Perempuan Narsis, perempuan yang mumuja kecantiakannya secara membabibuta. Bahkan ia menghalalkan segala cara demi kecantikannya itu, banyak sudah perempuan dioprasi plastik—tujuannya demi mempercantik wajahnya, ini melawan kodrat—kecantikan wajah adalah anugrah dari Tuhan tak usah lagi diubah-ubah. Ada pula yang mengedit wajahnya melalui seluler tujuannya agar ia tampak cantik—kendati hanya di media sosial. Bahkan baru-baru ini muncul tongsis (tongkat narsis) yang dipergunakan untuk memotret wajah diri sendiri—melalu seluler, smart phone.”
“Oooh, begitu,” gumamu, melunak.
“Dan engkau terberkati. Sebab, wajahmu telah cantik dengan sendirinya. Namun, tatalah jiwamu, agar engkau tidak terlalu terlena oleh kecantikanmu sendiri. Aku hanya khawatir, apa yang terjadi pada Dewi Narsis terjadi pula pada dirimu,” kataku, sambil tertawa ringan.
Ketawa renyahnya meledak, dan seketika matahari pun padam. Karena hari telah terjaring malam.
Dalam suatu hempasan, kecantikanmu membayang dalam benakku. Dan aku tak lagi bisa membedakan, kecantikan dari ketidak cantikan. Sebab, tiba-tiba semua wajah menjadi wajahmu. Barangkali aku telah menjadi gila. Barangkali?
Oleh: Agus Hiplunudin