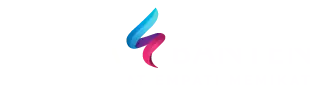Di masa hidupnya, seorang filsuf Yunani dan sekaligus tokoh Sophist yang bernama Protagoras (480 -410 SM) telah meluncurkan konsepsi pengetahuannya yang terkenal: Homo Mensura. Konsep “Man, the measure of all things” atau yang berarti manusia adalah ukuran bagi segala-galanya, kemudian menjadi landasan para filsuf modern bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau dogma-dogma langit, juga bukan dari kekuasaan feodal, melainkan dari diri manusia sendiri. Manusia diunggulkan menjadi makhluk otonom yang menentukan dirinya sendiri.
Maka di zaman Renaissance yang berlangsung antara 1400 hingga 1600 Masehi, kita tahu bahwa manusia di era itu dibetot untuk berontak melawan spirit Abad Pertengahan yang masih berdiri di atas dogma-dogma agama dengan metodenya yang skolastik. Jargon Homo Mensura seolah menjadi lonceng Renaissance yang mendorong manusia untuk melakukan “kelahiran kembali” dan pulang melihat kejayaan era Neo-Platonisme dalam sejarah kebudayaan Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh kebudayaan Barat seperti dibangunkan dari tidur panjang. Bermula dari Italia, lalu melebar ke negara-negara Eropa lainnya, sejumlah kemajuan melesat di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni dan kehidupan sosial lainnya. Lihatlah karya-karya seni yang dilahirkan Leonardo da Vinci dan Leon Battista Alberti. Baca juga karya-karya sastra dari Francesco Petrarca atau karya-karya filsafat dari Francis Bacon. Dari sana kita bisa melihat bagaimana manusia harus bisa mengembangkan perspektif-perspektif baru terhadap benda-benda maupun realitas, juga sekaligus menunjukkan bagaimana pengetahuan menjadi kekuasaan.
Sejak era Renaissance, manusia terus mendeklarasikan diri sebagai faber mundi (pencipta dunia). Manusia bukanlah sekadar viator mundi (peziarah dunia). Bermula dari ditemukannya mesiu, seni cetak, dan kompas, manusia terus merangsek menjadi penguasa dunia. Mesiu mengakhiri feodalisme. Seni cetak mengakhiri eksklusivisme pengetahuan oleh sekelompok elit dan membiarkan pengetahuan menyebar luas di tengah masyarakat. Kompas telah memberi navigasi yang akurat, yang mendorong manusia mampu melakukan perjalanan jauh dan penjelajahan dunia. Cakrawala berfikir manusia menjadi terbuka luas dan terbentang jauh. Manusia telah menjadi “Faber Mundi”. Antroposentrisme menggeliat dan menerjang dinding-dinding zaman.
Itulah sedikit potret “hijrah” dalam sejarah kebudayaan masyarakat Barat. Pemutusan diri terhadap masa lalu yang membuat kondisi aktual berada dalam status qua, tanpa kemajuan, dan tidak terjadi peningkatan kreativitas dalam kehidupan, hijrah berarti melakukan perjalanan baru ke arah yang baru. Hijrah berarti pulang ke pencapaian-pencapaian masa lalu yang baik dan menghadirkannya kembali dalam situasi yang baru dengan semangat yang baru.
Lalu, bagaimana Islam memberi konteks pada terminologi hijrah? Secara bahasa, hijrah berarti pindah ke negeri lain. Memutuskan. Meninggalkan. Berpisah (dengan pasangan) tanpa menceraikan. Berjalan. Namun demikian, peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekkah ke Madinah, sejatinya telah menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan transformasi keIslaman agar menjadi lebih baik dan aktual. Umat Islam ditantang untuk menginternalisasi pergerakan aspek spiritualitas dalam modus keber-agama-an. Modus keber-agama-an sebagai cara mengada manusia mengatasi “ketidakteraturan” dan “ketidakmenentuan” dalam dirinya haruslah mengalami prosesi hijrah dari waktu ke waktu.
Peristiwa hijrah Rasulullah yang terjadi sekitar tahun 622 Masehi itu, sungguh berkesan bagi umat Rasulullah sehingga ketika terjadi perencanaan penyusunan kalender versi Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab, momentum hijrah itu oleh Ali bin Abi Thalib diusulkan sebagai awal penghitungan kalender hijriyah dan akhirnya disepakati. Bukan momentum kelahiran Muhammad atau momentum di saat Muhammad menerima wahyu pertama kalinya atau momentum wafatnya Muhammad. Hijrah Rasulullah dari Mekkah ke Madinah merupakan titik tolak bagaimana dakwah Islam dijalani dengan strategi-strategi yang terukur, hingga kemudian Rasulullah mengajukan model-model masyarakat madani serta sistem pemerintahan yang memiliki daya diplomasi tingkat tinggi. Tanpa adanya momentum hijrah, sulit rasanya dibayangkan Islam bisa menjadi agama yang tumbuh merata di atas muka bumi ini.
Lahir di tengah kondisi kekufuran dan kejahiliyahan yang akut, penistaan kaum anak dan perempuan, sistem perbudakan yang menggila, Islam lalu menjadi oase. Ia hadir untuk menjelaskan kebuntuan-kebuntuan zaman yang dihadapi akibat manusia telah menjadi penguasa atas manusia dan penakluk alam. Islam menegaskan diri sebagai agama hanif, yang berisi ajaran-ajaran kepasrahan total hamba kepada Allah Sang Pencipta, namun aktif dalam ikhtiar-ikhtiar manusiawi sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka iman, sebagai infiltrator yang menjaga keseimbangan peran kehambaan dan kekhalifahan, menjadi mesin yang harus dijaga dan digerakkan untuk melahirkan energi ihsan dan pusaka ikhlas.
Di sinilah kita bisa melihat Islam memberi arti bagi upaya menanggulangi efek negatif antroposentrisme, yaitu ketika hijrah juga digerakkan untuk melahirkan kesalehan sosial dan kesalehan spiritual. Antara penghormatan terhadap kinerja manusia dan kepatuhan pada takdir Allah. Maka sesungguhnya kita butuh satu prosesi hijrah dari luar ke dalam, menukik ke kedalaman jiwa melalui jalan spiritual. Apa itu jalan spiritual, mari kita simak syair Jalaluddin Rumi berikut:
“Jalan spiritual adalah menghancurkan tubuh dan setelah itu memperbaikinya demi kemakmuran
Hancurkan rumah itu demi harta keemasan, dan dengan harta itu pula bangunlah rumah yang lebih baik daripada yang sebelumnya
Bendunglah air dan bersihkanlah dasar sungai, kemudian biarkanlah air minum mengalir ke dalamnya
Torehlah kulit dan cabutlah duri, kemudian biarkan kulit segar tumbuh menutupi luka.”
Jalaluddin Rumi, penyair mistik terbesar Persia yang lahir pada tahun 1207 di Balkh, sebuah kota di provinsi Khurasan, Persia Utara, memberi kita kesan kuat bahwa manusia harus terus menerus melakukan hijrah spiritual agar manusia bisa melihat bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Dengan demikian, jiwa manusia terus mencari dan mencari. Estafet hijrah pun terjadi.
Dalam syair lainnya Rumi pun menjelaskan:
“Para raja menjilat bumi tempat pekan raya terjadi
Karena Tuhan telah bercampur dalam bumi yang berdebu
Seteguk keindahan tercecap dari cawan pilihanNya
Inilah dia, cinta terkasih, bukan bibir tanah liat ini
Yang kauciumi dengan ratusan kenikmatan
Lalu bayangkan, apa yang mesti terjadi bila dirimu suci!”
Ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni, dan media kehidupan sosial lainnya kini semakin maju berkat pesatnya kemajuan teknologi di bidang komunikasi, informasi, dan transportasi. Tentu tantangan Islam agar bisa mengajak umatnya tidak larut dalam kemajuan dunia menjadi persoalan sendiri, agar di sisi lainnya umat Islam tidak sampai ketinggalan zaman. Umat Islam perlu setepat mungkin memaknai firman Allah dalam surat Al Qashash, ayat 77: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
Estafet hijrah, dengan demikian, harus terus dipertahankan di setiap jiwa manusia. Kerusakan di muka bumi terjadi ketika estafet hijrah telah berhenti, sehingga tidak ada lagi kemajuan-kemajuan kehidupan di muka bumi. Namun kerusakan di muka bumi ini juga terjadi ketika estafet hijrah dilakukan secara berlebihan, sehingga kemajuan-kemajuan yang dilahirkan hanya berbuah kesombongan yang menabrak batas-batas keniscayaan manusia sebagai hamba dan khalifah sekaligus. Dalam pengertian tertentu: manusia mungkin perlu hadir sebagai viator mundi, namun sekaligus sebagai faber mundi.###
Oleh: Chavchay Syaifullah
*Chavchay Syaifullah merupakan sastrawan dan budayawan. Kini sedang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Banten. Tulisan ini merupakan teks orasi budayanya yang ia sampaikan dalam acara “Peringatan Tahun Baru Hijriah Ke-1440” di Pondok Pesantren La Tansa, Cipanas, Lebak, Banten, Kamis, 13 September 2018.