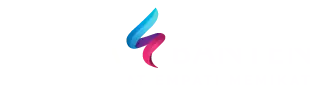Pelitabanten.com – Diusulkan pada tahun 2012 dan secara resmi diadopsi pada Januari 2016, Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) menetapkan prioritas United Nations Development Programme (UNDP) untuk memimpin tindakan nyata di lapangan yang menyerukan penghapusan kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030, bersama dengan lima belas target lainnya. Dengan mengusung poin pertama berjudul “No Poverty”, seluruh bangsa diharapkan berupaya mengurangi angka kemiskinan di negaranya.
Namun dalam penerapannya, hal tersebut mungkin dapat diupayakan secara signifikan oleh para anggota PBB yang tergolong negara maju, meskipun masih diakui sulit. Bahkan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengakui bahwa semakin sulit mencapai SDGs terutama di pandemi covid-19 saat ini, yang mana perekonomian jutaan orang terdampak. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang justru kewalahan dalam mencapai target tersebut. Kemiskinan secara global memiliki perbandingan jumlah dan tingkatan yang beragam di setiap negara, sehingga sulit untuk benar-benar memastikan kemiskinan secara rata terhapus di tahun 2030.
Penyebab kemiskinan secara global pun beragam, yang mana salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran sendiri memiliki banyak faktor, seperti kurangnya lahan pekerjaan hingga tingkat pendidikan. Penyebab kemiskinan di setiap negara pun juga berbeda-beda, baik dari segi struktural maupun kultural. Variabel dari misi penghapusan kemiskinan ini sangat banyak dan bercabang apabila kita telusuri lebih jauh. Belum lagi penyelesaian masalah satu variabel memerlukan waktu yang tidak sebentar, apalagi mencapai target “No Poverty” yang sesungguhnya. Terdengar pesimis, atau justru realistis?
Realitanya, SDGs ini pun mendapat kritikan dari Noam Chomsky, seorang ahli linguistik asal Amerika Serikat. Chomsky berpendapat mustahil untuk mencapai tujuan tersebut dengan strategi bisnis PBB yang seperti biasa dengan basis pembangunan, dimana ketimpangan pendapatan adalah masalah yang tidak ada habisnya. Chomsky juga menilai bahwa visi yang secara repetitif disebarkan oleh PBB kepada seluruh dunia ini memiliki konsep yang kabur dan tak jelas. Padahal, pembangunan yang dilakukan di sejumlah negara terjadi karena terdapat kepentingan kapitalisme. Kemudian agenda penghapusan kemiskinan ini mendorong seluruh negara anggota untuk melakukan pembangunan secara masif agar mencapai target di tahun 2030. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana bisa kita menemukan jalan keluar untuk menghapus kemiskinan menggunakan solusi “pembangunan” yang merupakan penyebab kemiskinan dan ketimpangan? Apakah isu No Poverty bukanlah isu negara berkembang, melainkan hanya sekedar agenda negara maju?
Permasalahan ini menarik untuk dilihat dari dua teori. Apabila melihat dari teori modern, maka negara berkembang lah yang harus menyesuaikan dengan perkembangan negara maju agar kemiskinan dapat berkurang seperti yang terjadi di negara maju. Sementara apabila kita melihat dari teori ketergantungan yang akarnya adalah pemikiran Karl Marx, kemiskinan yang terus terjadi dan menjadi masalah yang tidak ada habisnya adalah akibat dari negara maju yang terus mengeksploitasi negara berkembang. Dengan begitu, yang terjadi adalah negara berkembang mau tidak mau secara ekonomi dan politik terus dan tetap bergantung kepada negara maju untuk tetap berkembang.
“Blueprint” PBB ini terdengar wajar dan umum sebagai gambaran kondisi dunia yang baik. Namun apabila kita melihat realitas yang ada, “blueprint” ini tidaklah mewakili suara mayoritas di seluruh dunia, dimana mayoritas adalah mereka yang dieksploitasi dan ditindas dalam kondisi perekonomian dan perpolitikan global saat ini. Isu ini menjadi paradoks ketika tujuan “No Poverty” disudutkan kepada negara-negara berkembang agar mengupayakannya, dan di sisi lain ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang yang terus tereksploitasi sangatlah besar. Apalagi, banyak perusahaan multinasional dan negara yang menaruh modal di visi ini, karena sejatinya PBB tidaklah menghasilkan uang tetapi mendapatkan pemasukan dari berbagai pihak. Tentu tidak ada yang mau merugikan pihak yang telah memberi modal, dan tentu tidak ada pihak pemberi modal yang tidak menerima keuntungan. Ketika visi ini seharusnya fokus untuk masyarakat di seluruh dunia, justru agenda ini digunakan sebagai ruang perkembangan modal oleh berbagai perusahaan multinasional. Tidak heran apabila banyak yang menilai bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) adalah visi pembangunan yang penuh paradoks dan memiliki warna neoliberal di baliknya.
Meskipun ada banyak faktor terhambatnya penanggulangan kemiskinan setiap negara, baik dari sisi struktural maupun kultural, perjalanan pembangunan setiap negara memiliki start point, progress, dan kapasitas yang berbeda-beda. Maka dari itu, sangat sulit untuk memaksakan negara berkembang untuk melakukan pembangunan seperti yang dilakukan oleh negara maju, atau memaksakan negara yang baru berdiri di abad ke-20 untuk melakukan pembangunan seperti negara yang sudah berdiri sejak beberapa abad sebelumnya. Kondisi yang dicita-citakan memang mustahil untuk dicapai cepat, namun tidak mustahil apabila terdapat sinergitas antar para stakeholder yang tidak saling menjatuhkan, sehingga komitmen untuk mencapai target terus berkelanjutan. Dengan ini, pemerintah sebaiknya mengobrak-abrik dulu perihal penerapan SDGs tersebut agar kebijakan yang dijalankan menyesuaikan iklim negara masing-masing. Tanpa adanya peraturan, ketentuan hukum, dan kebijakan yang jelas dan kokoh, maka konsep Sustainable Development Goals (SDGs) ini hanya menjadi sebuah konsep utopis tanpa ada perwujudan nyata yang berhasil.
 Penulis: Rahmah Ramadhani (Mahasiswi Ilmu Politik asal Kota Tangerang)
Penulis: Rahmah Ramadhani (Mahasiswi Ilmu Politik asal Kota Tangerang)