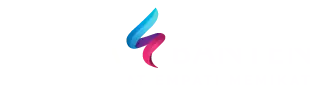Pelitabanten.com – Politik identitas dan nasionalisme mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir, baik dalam praktek maupun studi keilmuan dibidang politik dan sosiologi. Dalam studi pasca-kolonial politik identitas dan sosiologi sudah lama digeluti. Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C Spivak adalah nama-nama yang mendalami hal tersebut.
Sumbangsih mereka dalam meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya. Sementara dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of identity). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.
Pemahaman politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik kekinian. Karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.
Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan Politik identitas adalah memberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.
Sementara itu, bagai mana Nasionalisme berperan dalam praktek politik? Dalam antropologi, nasionalisme didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang beranggapan bahwa tapal-tapal batas budaya mesti bersepadanan dengan tapal-tapal batas politik,artinya bahwa negara harus mencakup hanya orang yang “berjenis sama” (Gellner 1983). Nasionalisme muncul sebagai tanggapan terhadap industrialisasi dan keterceraian orang-orang dari rupa-rupa ikatan primordial kepada kekerabatan, agama dan komunitas lokal. Peran ideologi nasionalisme dalam politik di Indonesia dimulai oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi Budi Utumo. Organisasi ini kemudian dipandang sebagai lambang kelahiran kesadaran nasionalisme di antara kaum pribumi dengan mencetuskan “Sumpah Pemuda” sebagai suatu komitmen politik mengaspirasikan semangat nasionalisme mereka.
Politik Identitas dan Nasionalisme Di Indonesia
Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan. Sedangkan nasionalisme di Indonesia awal mulanya merupakan idelogi bentuk perlawanan tehadap kolonialisme yang dimulai dengan penerbitan koran Medan Prijaji milik pengusaha pers dan jurnalis pribumi pertama R.M. Tirtoadisoerjo. Sikap radikalnya dituangkan dalam tulisan-tulisan yang banyak menyerang pejabat-pejabat Hindia Belanda serta pengungkapan-pengungkapan skandal-skandal korupsi di lingkungan birokrasi kolonial. Akibatnya, tahun 1912 surat kabar ini dilikuidasi dengan alasan utang dan penipuan, dan Tirtoadisoerjo dibuang ke Ambon.
Era politik kontemporer saat ini politik identitas mengancam sikap nasionalisme dan pluralisme yakni sebuah realitas kegamangan yang dialami bangsa Indonesia terkait menguatnya politik identitas. Agnes Heller (dalam Abdillah, 2002: 22) mengasumsikan politik identitas sebagai politik yang memfokuskan pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis. Oleh karena itu, bila dilacak dari sejarah Indonesia politik identitas yang muncul cenderung bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik. Terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme, maka politik identitas dapat menjadi bahan kajian yang menarik untuk ditelaah jika dihubungkan dengan penguatan nasionalisme bangsa.
Pola-pola operasionalisasi politik identitas ini dapat kita jumpai pada realitas yang terjadi di masyarakat ditunjukkan dengan banyaknya perbenturan kepentingan dan fenomena ego sektoral, antara lain: Pertama, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bergeseranya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing. Politik Identitas ini ditampakkan dengan maraknya isu etnisitas dan gejala primordialisme yang diusung melalui isu “putra daerah” dalam menduduki jabatan publik, isu etnis asli dan anti pendatang, dan isu etnis mayoritas dan minoritas. Kedua, wilayah agama sebagai lahan beroperasinya politik identitas.
Dalam konteks Indonesia politik identitas itu dilakukan oleh kelompok mainstream, yaitu kelompok agama mayoritas dengan niat menyingkirkan kaum minoritas yang dianggapnya menyimpang atau menyeleweng. Bersamaan dengan ini munculnya gerakan-gerakan radikal atau semi radikal yang berbaju Islam di Indonesia. Ketiga adalah wilayah hukum.
Wilayah hukum yang dimaksud adalah wilayah paduan antara wilayah negara dan agama, karena masing-masing memiliki aturannya sendiri. Pada sisi ini, politik identitas beroperasi dengan cara pembagian kekuasaan, di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya secara partikular.
Kemungkinan modus kita akan menjadi dasar bagi hubungan politik identitas yang dibangun sangatlah besar. Namun demikian, hal ini tidak akan terjadi seandainya kepentingan dari politik identitas etnis yang bersifat minoritas tidak terjembatani melalui pengakuan hak-haknya untuk berpartisipasi di wilayah pembuatan keputusan hukum secara bersama.
Berdasarkan pada ketiga pola operasionalisasi tersebut, politik identitas cenderung mendistorsi wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun oleh bangsa Indonesia. Kemajukan dalam ikatan persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar tumbuhnya nasionalisme tidak pernah tuntas dalam proses pendefinisian tentang identitas ke-Indonesiaan.
Issu Politik Identitas dan Nasionalisme dalam Pilkada 2017
Masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan kelompok masih jadi komoditas politik. Dalam kontestan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 20117 ada yang berbeda dibandingkan pilkada sebelumnya. Hal ini dikarenakan Issu sara dan agama menjadi ikon politik dalam berbagai manufer kampanye.
Penggunaan politik SARA dan keagamaan hal dalam pilkada serentak 2017 dikarenakan munculnya salah satu kandidat Gubernur yang beragama non islam dan dari kalangan minoritas. Dalam perhelatan pilkada 2017 terutama Pilkada DKI Jakarta yang dipicu pasangan Basuki –Jarot menjadi titik awal tradisi politik baru dalam sistem kampanye politik. Tradisi politik yang menguatkan politik SARA membuat Indonesia akan kehilangan integritas kebangsaan yang digagas pendiri bangsa yang tertuang dalam konsep Bhineka Tunggal Ika. Dengan kampanye Masing – masing kubu pendukung menggunakan cara – cara yang kurang sehat dan saling menjatuhkan dengan menggunkan kekuatan – kekuatan identitas seperti SARA yang melekat pada rakyat bangsa Indonesia. Praktek politik tersebut sangat rentan konflik dan perpecahan sesama anak bangsa. Politik SARA lebih mengeksploitasi perbedaan agama dan etnis bahkan ideologis dalam meraup aspirasi masyarakat dalam proses mementukan pilihan politik. Proses politik yang mengekploitasi issu – issu SARA, suku dan agama yang terjadi di perhelatan Pilkada DKI Jakarta kemarin menjadi issu sentral awal dalam babak tradisi politik baru yang kemungkinan berlanjut pada pilkada berikutnya bahkan ke pilpres 2019 nanti.
Berbeda dengan pilkada serentak yang digelar sebelumnya segala aktifitas kampanye politik tidak mengarah pada politik SARA melainkan lebih cenderung pada orientasi politik aliran yang menekankan afiliasi identitas keberagamaan (santri vs abangan) dalam menentukan pilihan politik. Seperti halnya pada kontestan pilpres, Kemenangan pasangan SBY-JK (60,62%) atas Megawati-Hasyim Muzadi (39,38%) pada putaran kedua Pilpres 2004 telah dipahami sebagai manifestasi senja kala politik aliran. Koalisi gerbong nasionalis dan santri kala itu berhasil diatasi sosok SBY-JK yang akar ideologisnya mungkin kurang mengakar dibandingkan Mega-Hasyim.
Tesis ini teruji pada ajang Pilpres 2009. Gerbong politik Mega-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto tidak mampu mengimbangi magnet politik SBY-Boediono yang meraup suara 60% lebih. Fenomena politik ini menandakan berkurangnya signifikansi faktor sosiologis dalam menentukan perilaku pemilih sebagaimana ditemukan Mujani dkk (2012).
Dengan demikian betapa pentingnya peristiwa issu – issu Pilkada 2017 terutama wacana politik pilkada DKI Jakarta yang mampu menyedot perhatian berbagai kalangan umat beragama. Oleh karenanya kita sebagai anak bangsa harus mampu mawas diri dan melek dalam hal jati bangsa kita. Jangan karena politik kita kehilangan integritas kebangsaan yakni Keindonesiaan.
Oleh: Wakyudi, MSi
Penulis adalah Peneliti di Yuwana Skripta Institute
dan pengamat Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah